Oleh: Wahyu Rizkiawan
Buku Pendidikan yang Memerdekakan menarik untuk dibaca, baik isi cerita maupun teknik penyampaiannya. Sebab ia tak terjebak pada penyampaian berorientasi howto. Namun bercerita secara just show don’t tell.
Membaca buku Pendidikan yang Memerdekakan langsung mengingatkan saya pada pertanyaan Pak Haidar Bagir dalam buku terbarunya, Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia. Dalam buku tersebut, tokoh tasawuf sekaligus pendiri Mizan Group itu bertanya; mendidik anak untuk (menjadi) pintar atau (menjadi) bahagia?
Tentu saja, semua akan menjawab mendidik anak untuk bahagia. Sebab, pintar tak mesti bahagia. Sementara bahagia belum tentu pintar. Meski tentu saja, pintar sekaligus bahagia punya maqom yang lebih mulia.
Sebab, jika diiringi karakter-karakter tertentu, kepintaran membantu terwujudnya bahagia. Istilahnya, anak pintar yang punya karakter-karakter tertentu, punya peluang bahagia lebih besar dibanding anak kurang pintar.
Masalahnya, banyak sekolah formal saat ini yang mendorong anak untuk pintar, dengan cara yang kurang membahagiakan. Sehingga memicu anak kehilangan peluang memiliki karakter yang mendukung kebahagiaan.
Benar kata Howard Gardner bahwa anak-anak pergi ke sekolah dan kuliah hingga lulus, tapi tampaknya tak terlalu peduli menggunakan pikiran mereka. Sebab sekolah tak memiliki dampak positif jangka panjang seperti yang seharusnya.
KBQT menjadi antitesis dari sekolah yang dimaksud Gardner. Dan buku Pendidikan yang Memerdekakan ini, membuat kita tahu tentang bagaimana membangun atmosfer belajar secara gembira dan bahagiawi.
Buku ini menceritakan bahwa Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT), tak hanya mendidik anak untuk bahagia. Tapi menjadikan “rasa bahagia” sebagai landasan utama proses pendidikan itu dijalankan. Seperti disinggung Haidar Bagir.
KBQT menjadi kritik atas maraknya sekolah formal yang ahli mencetak anak menjadi robot tak kontekstual terhadap lingkungan masyarakat. Sebab, selain memberi kebebasan anak belajar sesuai minat (dan bertanggung jawab atas pilihannya itu), KBQT juga menjadikan lingkungan sebagai bagian penting proses pembelajaran.
KBQT yang lahir dari rahim Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), tentu tak bisa lepas dari unsur-unsur desa dan sawah. Mengingat, SPPQT adalah lembaga civil society yang lahir dari dalam desa.
Sehingga sawah, desa, pengairan beserta masalah-masalah yang dihadapi secara head to head masyarakat, benar-benar menjadi bagian penting dari proses belajar di KBQT. Sehingga KBQT memang memegang teguh kontekstualitas.
Selain kontekstual, KBQT juga menjadi antitesis dari paradigma IQ. Sebab ia menghargai kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) ala Howard Gardner. Yakni kecerdasan tak hanya sebatas pada IQ. Tapi meliputi banyak kecerdasan.
Istilah alternatif, oleh KBQT, tak dimaknai sekadar beda dari sekolah lain. Sebagai sekolah ultra alternatif, KBQT menghadirkan sekolah terbuka untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermutu. Ya, tak sekadar beda. Tapi lebih bermutu. Artinya, kualitas sudah dipersiapkan sejak dari niat dan pikiran.
Memang benar. Selama ini, pendidikan formal tak benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (secara kontekstual). Tak ada sekolah yang mengajarkan materi tentang desa, meski sesungguhnya sekolah itu berdiri di sebuah desa.
Sekolah formal, diakui atau tidak, selama ini hanya “menyelamatkan” kita secara sosial formalistis sebagai kaum terdidik. Tapi bukan kaum yang keterdidikannya memiliki manfaat secara kontekstual terhadap kehidupan sehari-hari.
Di sanalah kekurang-bermutuan sekolah formal benar-benar terbaca dan langsung di-counter oleh KBQT. Lembaga berbasis komunitas ini berdiri tegak dan bergerak mengisi celah-celah kekurangan sekolah formal dengan giat-giat alternatif yang dijalankan.
Serupa konsep Desa Mengepung Kota ala Mao Tse Tung, KBQT bergerak dari basis pedesaan. Itu terlihat dari visi jangka pendek dan jangka panjangnya; yang mana, untuk jangka pendek: menyelesaikan masalah praktis di Desa Kalibening. Sementara jangka panjang: membangun masyarakat pembelajar.
Dalam buku ditulis Ahmad Bahruddin dkk ini, ada dua bab penting yang menampakkan keistimewaan KBQT. Yakni bab Prinsip Belajar dan Praktik Belajar. Dua bab ini adalah bagian inti yang membuat pembaca tahu, betapa kegiatan-kegiatan di KBQT benar-benar tidak mainstream dan ultra alternatif.
Pada bab Prinsip Belajar, misalnya, ada 4 poin yang menjadikan KBQT sebagai lembaga pendidikan alternatif. Sebagai wahana belajar yang memang tak akan bisa ditemui di lembaga pendidikan mainstream manapun. Keempat poin itu adalah;
Pembebasan
Kurikulum dianut KBQT berbeda dengan kurikulum nasional. Kurikulum nasional menempatkan siswa sebagai objek pengajaran. Memposisikan siswa sebagai sosok harus dijinakkan. Siswa hanya wadah kosong siap isi. Sedang guru, jadi satu-satunya sumber ilmu yang mengisi wadah berupa siswa tersebut.
Sementara KBQT, siswa diposisikan sebagai subjek. KBQT memberi ruang penuh agar siswa membaca dan menangkap kehidupan. Di KBQT, siswa adalah subjek yang aktif berpikir. Sementara guru hanya pendamping. Bukan mesiah pemberi ilmu. Dan di sini, paradigma Multiple Intelligences benar-benar diterapkan.
Kontekstual
KBQT, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, sejak awal punya tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Sehingga proses pembelajaran dalam KBQT, punya relevansi dan kontekstual terhadap lingkungan tempat ia berada. Hasilnya, siswa tidak hilang dari konteks hidup dan komunitas di mana ia tinggal.
Keberhasilan seorang siswa atau sebuah institusi pendidikan seharusnya diukur dengan seberapa besar dampak yang bisa ia sumbangsihkan bagi komunitasnya, bagi lingkungannya (hal: 39). Menurut saya, itu kritik utama terhadap lembaga pendidikan formal.
Kegembiraan
KBQT lembaga pendidikan berbasis kegembiraan. Sebab, tak ada pemvonisan ataupun dikte penyeragaman dalam proses evaluasi dan penilaian. Setiap anak belajar sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Tentu, proses ini memicu hadirnya rasa bebas dan gembira.
Di KBQT, tak ada sistem penilaian melalui tes atau ulangan atau tryout untuk mengukur pencapaian siswa. Sebab pencapaian siswa, diukur dari karya yang dihasilkan. Karya berbentuk apapun — novel, lukisan, penelitian atau film — akan diapresiasi guru pendamping. Kegembiraan, tentu bakal dirasakan karena masing-masing siswa bergerak sesuai ghirah-nya.
Kolaborasi
Ini menjadi pelengkap 3 prinsip belajar yang sebelumnya disebutkan. Demi capai proses belajar yang merdeka, kontekstual dan gembira, kolaborasi antara stakeholder adalah ujung tombak yang mampu membuat KBQT bergerak hingga saat ini.
Stakeholder, dalam hal ini; pendamping, murid, orang tua, serta pengelola komunitas, bersatu padu memaksimalkan peran masing-masing. Di KBQT; pendamping (guru), orang tua, dan pengelola komunitas punya peran yang sangat vital.
Sedang dalam bab Praktik Belajar, terdapat 16 poin penting yang menunjukan betapa 4 prinsip belajar di atas benar-benar diaktualisasikan di dalam keseharian KBQT. Upacara Tanpa Baris-berbaris dan Ujian Nasional Semaunya adalah dua contoh poin paling menarik dibaca.
KBQT sama sekali tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan, para warga belajar untuk mengikuti ujian nasional. Tapi tentu saja KBQT tetap menawarkan dan memfasilitasi jika anak-anak berminat. Jadi proses ujian nasional di KBQT memang betul-betul semau-mau anak. Bukan semau-mau lembaga maupun negara (hal: 92).
Pendidikan, kata Haidar Bagir, adalah proses memanusiakan manusia. Untuk mengaktualkan berbagai potensi sehingga menjadi manusia sejati. Manusia yang sejahtera dan berbahagia. Dan KBQT telah melakukan itu.
Itulah keistimewaan KBQT, di saat seluruh sekolah — entah formal entah non formal — di Indonesia memandang Ujian Nasional sebagai sesuatu yang amat penting dan menentukan, KBQT tidak. Bahkan, menganggap UAN sesuatu yang sunah muakad pun tidak.
Saat ini, ketika euforia penghapusan UAN masih bergema di tiap jengkal dinding kantor kepala sekolah, KBQT sudah mengawalinya jauh-jauh hari. 17 tahun lalu, KBQT sudah memandang sinis UAN yang terkenal bengis tersebut.
Konsep UAN yang bertolok ukur pada keseragaman kompetensi siswa memang tak sesuai dengan prinsip belajar merdeka yang dipeluk KBQT. Atau dalam istilah lain, UAN tidak adil sejak dalam konsep. Sebab menyamaratakan evaluasi penilaian antara kawasan desa dan kota, sementara jelas keduanya bias kasta. Dan itu tak sesuai dengan KBQT.
Buku ini menarik dibaca, baik isi cerita maupun teknik penyampaiannya. Sebab, meski bukan buku fiksi, ia tak terjebak pada penyampaian ceramah berbasis howto. Sebaliknya, disampaikan secara just show don’t tell. Buku ini memperlihatkan apa yang terjadi di KBQT, bukan memberitahu bagaimana cara membuat sekolah. Itu yang membuat saya, secara personal, terkesima.
Memunculkan kembali serpihan utopia masa lalu
Tak hanya membuat saya terkesima. Buku ini membuat saya teringat cita-cita utopis dan utopia-utopia keinginan yang sempat tergurat dalam hati saya, beberapa tahun silam.
Akhir 2009, saat menjadi mahasiswa baru, saya bersama teman-teman himpunan mahasiswa Padangan Bojonegoro, punya keinginan membuat sekolah non formal yang di dalamnya, anak putus sekolah atau siswa-siswi SD dan SMP bisa belajar apa saja. Sesuai minat mereka.
Kami menjadikan Balai Desa Padangan sebagai tempat belajar. Tapi karena tak menemukan buku panduan atau guru yang bisa memberi pencerahan terkait kurikulum yang harus dipegang; sekolah non formal impian itu, pada akhirnya, berubah menjadi les-lesan biasa. Menjadi tempat les anak-anak sepulang sekolah.
Mungkin karena embrio cita-cita itu masih melekat di dalam hati, dan kebetulan bertemu pasangan yang memiliki gagasan dan cita-cita yang sama, pada 2015, sesaat setelah menikah, saya dan istri punya ide membikin sekolah non formal kecil-kecilan di rumah — sebagai bagian kecil dari komitmen berumahtangga.
Cita-cita itu amat sederhana sekali. Kelak, anak-anak kami dan anak-anak tetangga, akan menjadi siswa-siswi pertama di sekolah itu. Sekolah yang menjadikan bermain sebagai mata pelajarannya.
Awalnya, kami hanya menggelar koleksi buku kami untuk dibaca anak-anak tetangga di teras rumah. Satu dua anak datang. Lalu, banyak anak berdatangan. Kami membolehkan mereka belajar apa saja. Sesuai keinginan mereka.
Ada yang belajar ngaji. Menulis. Menyanyi. Mengenal dan menanam bunga. Membuat kue. Menggambar. Apapun, selama kami berdua bisa, kami berdua selalu bersedia mendampingi mereka.
Mungkin kami belum menemui buku pedoman yang pas. Atau minimnya SDM sebab hanya berdua menjalankannya, masalah muncul justru ketika Tuhan menitipkan anak pada kami. Hehe ~
Kami berdua sibuk mengurus anak. Sehingga kegiatan yang sebelumnya kami lakukan bersama-sama itu pun, mulai berkurang intensitasnya. Terlebih, ketika kami memutuskan untuk pindah rumah.
Beberapa hari lalu, saat saya menceritakan hasil pembacaan saya terhadap buku Pendidikan yang Memerdekakan ini pada istri, dia sangat senang sekali. Dia seperti menemukan apa yang dulu pernah kami berdua cita-citakan kala menjadi pengantin baru.
Buku ini tak hanya membuat saya mampu mengetahui titik beda antara sekolah alternatif dan sekolah formal biasa. Namun juga membuat saya kembali menemukan semangat yang dulu sempat saya dan istri saya cita-citakan bersama.
*Disalin dari: JURNABA
Memanusiakan Manusia melalui Pendidikan yang Memerdekakan
Hubungi kami
Alamat: Jl. Raden Mas Said No. 12 Kalibening, Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah
Contact List
Form Pendaftaran: linktr.ee/KBQT
Email: qaryah.thayyibah@gmail.com
WhatsApp: 085117202897
Kirim email
Copyright ©
KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH

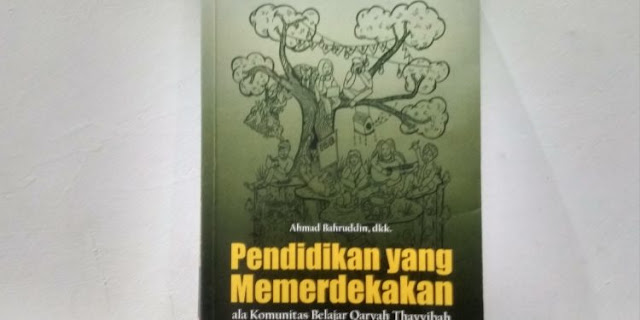

0 Comments